 sumber: unsplash.com
sumber: unsplash.comAda yang ganjil dari waktu yang kita jalani. Ia tak pernah benar-benar berlalu, juga tak pernah datang sepenuhnya. Dalam epos kehidupan, waktu tampak tak bertuan—berlari cepat tapi kehilangan arah. Dan kita menyebutnya “peradaban”, tapi seringkali yang ditemukan justru kelelahan kolektif, kegelisahan, dan rasa keterasingan di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur.
Sungguh, ini bukan hendak menebak masa depan seperti para futurolog kawakan semacam Alvin Toffler, John Naisbitt atau Yuval Noah Harari. Bukan. Tapi, mungkin, lebih ingin menggugat waktu kini, yang seakan menumpuk tanya tentang kemajuan yang mengikis kebermaknaan, tentang kecepatan yang menyingkirkan kedalaman, dan tentang pencapaian yang mengaburkan kebahagiaan.
Belum lama saya membaca Byung-Chul Han, filsuf kelahiran Korea yang bermukim di Jerman, ia menulis The Burnout Society, katanya masyarakat kini telah terperangkap dalam “tirani positivitas”—kewajiban untuk produktif, untuk selalu ‘bisa’, untuk terus berlari. Sebuah masyarakat yang, tak lagi dikekang oleh larangan atau represi seperti kata Foucalt, tetapi oleh kebebasan yang dimanipulasi: "I am free, therefore I must." Maka kelelahan bukan karena kerja paksa, melainkan karena manusia memaksa diri sendiri untuk bekerja tanpa henti.
Manusia menyebutnya ambisi. Yang dibungkus dengan slogan-slogan motivasi. Tapi di balik itu, mungkin tanpa sadar manusia sedang mengalami kehilangan yang tak kentara. Kehilangan keheningan, kehilangan momen kontemplatif. Apa yang disebut “kemajuan” ternyata tak serupa dengan “kebermaknaan”. Upaya manusia menaklukkan dunia melalui kerja dan produksi, justru kehilangan dimensi vita contemplativa, hidup yang merenung, yang mengendap, yang perlahan. Sebab, kini ia sudah menjadi homo faber—manusia pembuat—yang menciptakan banyak hal, namun lupa mengolah makna dari yang kita ciptakan.
Kita begitu sibuk menyusun masa depan, hingga lupa bertanya apakah masa depan itu benar-benar perlu? “Kemajuan”, mungkin tak lebih dari mitos yang diciptakan oleh zaman yang kehilangan arah. Saat segala sesuatu diukur dari akumulasi nilai, angka, ranking, bahkan kebahagiaan, maka eksistensi kita direduksi menjadi statistik. Kita menjadi barisan data, bukan lagi individu dengan sejarah dan imajinasi.
Pertanyaannya, masih mungkinkah manusia berhenti sejenak? Masih adakah ruang untuk diam yang tidak dituduh malas, atau istirahat yang tidak dicurigai sebagai kemunduran?
Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles menulis bahwa tujuan akhir manusia adalah eudaimonia—bukan sekadar kebahagiaan yang dangkal, tapi “hidup yang baik”, hidup yang dijalani dengan kebijaksanaan dan keutamaan moral. Aristoteles sedang menyatakan bahwa hidup bukan tentang efisiensi, melainkan tentang keberimbangan dan kelayakan.
Tapi siapa yang masih mau bicara tentang kelayakan, ketika dunia menilai seseorang dari angka?, bukan dari integritas? Sebuah zaman yang lebih percaya pada ranking Google Scholar, indeks Scopus, dan GDP daripada kejujuran nurani. Mahasiswa diajari bukan untuk berpikir, tapi untuk lulus cepat. Akademisi berlomba bukan dalam kebajikan, tapi dalam jumlah sitasi.
Tentu kita tak bisa menghindar dari banalitas dunia modern itu sepenuhnya. Hanya saja mungkin kita bisa merintis jalan kecil: jalan kesadaran yang tidak ditentukan oleh algoritma. Jalan perenungan yang tidak takut sepi.
Dalam dunia yang penuh narasi kemenangan, mungkin yang dibutuhkan justru narasi kehilangan. Karena di sana kita bisa mulai bertanya ulang: apa arti menjadi manusia? Apa arti cinta di tengah kecepatan? Apa arti beragama di tengah ritual yang terkadang kehilangan ruh? Apa arti keadilan di tengah sistem hukum yang mengukur manusia dengan uang dan pengaruh?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah beban, melainkan anugerah. Sebab hanya dengan bertanya, kita bisa menemukan kembali makna. Atau setidaknya, kita tidak kehilangan arah sepenuhnya.
Dunia memang semakin terfragmentasi—antara kerja dan rumah, antara identitas dan peran sosial, antara publik dan privat—maka mungkin yang kita butuhkan adalah ruang yang menghubungkan kembali.
Simone Weil pernah bilang “the soul’s first need is attention.” Mungkin tugas kita sebagai manusia zaman ini adalah kembali memberi perhatian. Kepada waktu. Kepada sesama. Kepada suara-suara yang nyaris hilang. Bukan atensi yang cepat dan impulsif seperti notifikasi, tapi perhatian yang tulus dan berdiam.
 sumber: unsplash.com
sumber: unsplash.comDalam kesunyian yang terhindarkan itu, barangkali ada obat yang kita cari. Dalam jeda yang dianggap gagal, mungkin ada keberhasilan yang sejati. Dalam pertanyaan yang tertunda, bisa jadi tersimpan arah yang kita rindukan.
Karena itu, menulis bagi saya bukan hanya soal kata-kata. Ia adalah cara untuk tetap waras di tengah kegilaan yang dilembagakan. Ia adalah doa yang dijahit dalam narasi. Ia adalah pengingat bahwa saya masih manusia, dan belum seluruhnya menjadi mesin.
Hari ini, di tengah berita yang terus menumpuk, dalam banjir informasi yang tak pernah surut, saya menulis bukan untuk menjelaskan dunia. Saya menulis agar dunia tak sepenuhnya gelap. Agar ada satu sudut kecil di benak pembaca yang bertanya, merenung, lalu—barangkali—tersenyum pelan.
Maka saya akhiri tulisan ini sebagaimana saya memulainya: dalam kesadaran bahwa waktu bukan sesuatu yang bisa dikuasai, tapi sesuatu yang bisa diberikan makna. Bahwa hidup bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang sejauh mana kita hadir. Hadir sepenuhnya, sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai rentetan nama di sebuah sertifikat penghargaan yang terus menilai.
Karena seperti kata T.S. Eliot, waktu kini dan waktu lalu, waktu yang akan datang—semuanya bertumpuk dalam satu ruang: ruang kesadaran. Dan mungkin, justru di sanalah hidup benar-benar terjadi. [ ]

 1 month ago
4
1 month ago
4























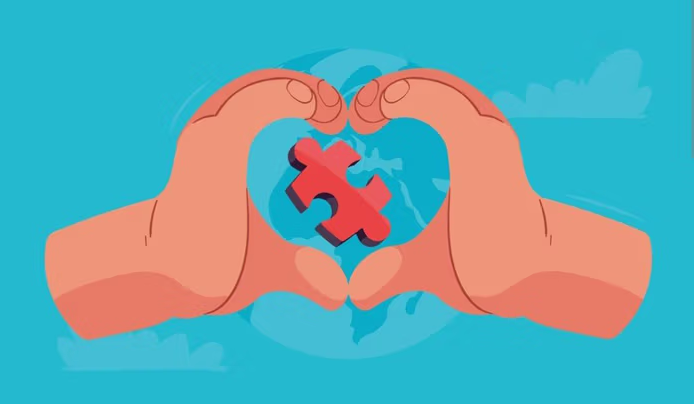















 English (US) ·
English (US) ·